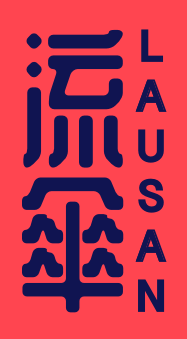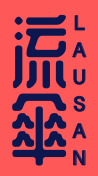Asli: Hong Kong’s Movement Must Stop Ignoring Migrant Workers
Penerjemah: Nadia Damayanti
Diterbitkan asli di openDemocracy
Diterjemahkan oleh sukarelawan di komunitas kami. Hubungi tim penerjemah untuk informasi lebih lanjut.
Pada tanggal 5 Agustus, lebih dari 350.000 pekerja mengikuti aksi mogok besar pertama kali di Hong Kong. Pada hari itu, seluruh penerbangan dan sistem transportasi kota dibatalkan karena adanya kekacauan di kota. Aksi mogok tersebut merupakan titik puncak dari berminggu-minggu protes yang dilangsungkan untuk menentang rencana amandemen pada undang-undang ekstradisi Hong Kong, yang akan memberikan kekuasaan sepenuhnya pada kepala badan eksekutif sebuah kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya yaitu untuk mendikte keputusan ekstradisi dan memotong badan legislatif Hong Kong. Aksi mogok tersebut merupakan wujud yang hebat mengenai solidaritas para pekerja dan mahasiswa, dan sebuah langkah ke depan yang penting dalam mobilisasi massa dalam protes tersebut. Namun, ada hal yang tidak biasa terjadi dalam sebuah demonstrasi, pada saat itu tidak ada tuntutan secara eksplisit mengenai kondisi dan kualitas tenaga kerja di Hong Kong. Dorongan untuk menjadi bagian otonomi dari China telah memobilisasi jutaan manusia untuk turun ke jalan tapi, pada saat yang sama, ada hal lain dalam solidaritas yang diabaikan dalam aksi ini.
Pekerja migran domestik yang datang dari negara-negara Asia Tenggara memiliki posisi yang unik namun sedikit terlupakan pada aksi yang terjadi di Hong Kong. Hampir 400.000 pekerja migran (lebih dari jumlah peserta yang mengikuti pemogokan), umumnya berasal dari Filipina dan Indonesia, bekerja di bawah tekanan dan upah sedikit di Hong Kong. Umumnya, para pekerja datang ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan yang lebih baik daripada yang ada di desa mereka, namun hampir 80 persen dari mereka hidup dalam hutang dan berlindung dalam praktek kerja yang eksploitatif dari agen rekrutmen. Berdasarkan laporan terakhir, pekerja migran berkontribusi lebih dari $12 juta untuk perekonomian Hong Kong.
Banyak dari pekerja memberikan dukungan pada protes dan persatuan pekerja migran di Hong Kong, beberapa berafiliasi dengan gerakan pro-demokrasi Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), terang-terangan mendorong anggota mereka untuk mengikuti demonstrasi langsung ke jalan. Namun adanya beberapa tekanan yang membatasi partisipasi mereka, serta tuntutan protes mereka yang belum secara langsung memberikan solusi pada permasalahan mereka. Beberapa juga ada yang tidak ikut bergabung karena takut apabila visa kerja mereka dicabut; konsulat negara Filipina telah mengirimkan peringatan kepada pekerja migran yang mengikuti demo. Clarisse*, seorang pekerja migran dari Filipina, mengatakan bahwa banyak majikan tidak mengizinkan pekerja migran untuk mengikuti aksi protes, dan beberapa majikan bahkan melarang mereka untuk mengambil cuti wajib mereka. Lagi pula, titik kumpul pekerja migran untuk melakukan demo merupakan area yang biasanya dijadikan area baku hantam antara polisi dan para peserta demo, sehingga pada akhirnya sedikit yang mengikuti aksi tersebut.
Peringatan palsu yang datang langsung dari pemerintah, bahkan ancaman pembunuhan, telah beredar tanpa nama di ranah media sosial yang akrab digunakan oleh pekerja migran seperti WeChat dan Whatsapp, berdasarkan Fish Ip, koordinator regional International Domestic Workers Federation (IDWF). Ada satu pesan yang secara spesifik bersifat ancaman yang bertujuan menyerang pekerja Nepal, India, dan Pakistan apabila mereka ikut berpartisipasi dalam aksi demo, banyak dari mereka bahkan bukan merupakan pekerja migran, hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan ras minoritas di Hong Kong menjadi target serangan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Laporan bahwa ada polisi Hong Kong yang menganiaya dan menahan penari yang berasal dari Filipina menjelang aksi mogok menimbulkan kegelisahan pada pekerja migran. Ancaman-ancaman lainnya dirancang sebagai pembalasan dari desas-desus yang menyebar bahwa etnis minoritas terlibat dalam penyerangan peserta aksi demo di Yuen Long.
Sikap masa bodoh masyarakat Hong Kong terhadap pekerja migran
Hong Kong masih dianggap sebagai tempat yang lebih baik untuk bekerja dan berorganisasi daripada pusat kegiatan migran yang lain seperti Dubai, walaupun tidak dipungkiri bahwa masih banyak kekurangan dalam hak dasar pekerja. Hope*, seorang dari Filipina yang telah bekerja di Hong Kong sejak tahun 1996, gelisah terhadap undang-undang ekstradisi yang akan menjadi akses utama untuk kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh pada buruh migran maupun penduduk lokal. Namun yang paling utama, ia khawatir apabila hak untuk berorganisasi dan bebas dalam berkumpul akan terancam karena undang-undang tersebut. Kantor konsulat jenderal Filipina memberitahukan kepada Hope bahwa aksi demo bukanlah persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja domestik. Namun Clarisse menolak sikap tersebut, “Kami hidup dan bekerja di Hong Kong, ini adalah rumah kedua bagi kami dan apapun yang akan terjadi di sini, kami juga yang akan terkena dampak dan imbasnya.”
Adanya sikap masa bodoh pada keadaan dan kualitas yang buruk yang terjadi pada pekerja migran di Hong Kong, aspirasi mereka diabaikan oleh gerakan pro-Demokrasi dan pemerintah. Meskipun begitu keadaan yang terjadi, wawancara dengan pekerja migran menjelaskan kompleksnya permasalahan pekerja migran yang melihat Hong Kong sebagai rumah kedua. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pekerja migran domestik memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi perempuan di Asia Timur (umumnya ibu-ibu) untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Dengan kata lain, migran, walaupun partisipasi mereka terbatas, memainkan peran yang penting dalam perekonomian dan aksi demo: pekerjaan mereka memungkinkan banyak keluarga untuk terlibat dalam aksi demo.
Hal ini umumnya membuat para wanita buruh migran domestik dari Asia Tenggara yang menanggung dampak dari proses dekolonialisasi Hong Kong yang belum kunjung usai.
Sementara, demo telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merundingkan kembali mengenai pemahaman mereka tentang permasalahan struktur permasalahan di Hong Kong, hak pekerja migran tetap menjadi titik kelemahan dalam aksi demo. Contohnya, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap kepolisian merupakan langkah baru dan kritis dalam radikalisasi. Namun aksi diam terhadap kondisi buruh migran menunjukkan bahwa adanya kelemahan yang terus terjadi dalam tuntutan peserta demo yaitu ketidakmampuan untuk mengenal bahwa kesengsaraan Hong Kong sesungguhnya terkait dengan eksploitasi ekonomi berskala global, dan dampak struktural dari bentuk-bentuk baru sistem kolonialisme.
Sring Atin, seorang pekerja domestik dan anggota dari Indonesian Migrant Workers Alliance (IMWA) yang mendukung aksi demo, mengatakan bahwa tuntutan pergerakan tidak secara konkret mengangkat isu dan permasalahan buruh migran. Perlawanan melawan kebijakan-kebijakan ekstradisi yang baru merupakan fokus utama pengerahan massa demonstran menurut Sring Atin, dan masih harus pula mengajak pekerja dalam mengangkat permasalahan buruh migran untuk memastikan bahwa kualitas dan kondisi kerja yang layak untuk komunitas-komunitas paling terpinggirkan.
Ketidakjelasan pada permasalahan menunjukkan sentimen eksklusif anti-asing merupakan konstitutif ideologi masyarakat lokal. Jiwa etnonasionalisme berhubungan dengan “identitas Hong Kong” telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok-kelompok lokal seperti Hong Kong Indigenous, kelompok yang mempromosikan ideologi yang bersifat anti-asing terhadap seluruh orang Cina Daratan. Sentimen eksklusif tersebut membuktikan secara halus dan dalam bermacam-macam maksud ketika hal tersebut berkaitan dengan permasalahan pekerja migran, yang isu-isunya hanya dilihat sebagai ‘penolong’ dalam perjuangan Hong Kong.
Kelas dan ras: apakah kelemahan dari pergerakan?
Hong Kong terjepit di antara perjuangan geopolitik antara Cina dan AS. Wilfred Chan bertanya dalam Dissent apa artinya untuk masyarakat kota dalam “menciptakan sebuah sebuah tatanan politik baru yang bersifat anti-kapitalis dan anti-otoriter sebagai bentuk untuk bertahan hidup dalam situasi yang belum jelas?” jawabannya terletak pada pergerakan kelas pekerja di Hong Kong dan ini akan memerlukan penataan sebuah koalisi baru. Potensi sebuah politik yang bersifat anti-kapitalis sudah ada saat ini, di Hong Kong di mana buruh migran dan warga lokal bertemu dan menghabiskan waktu bersama di setiap jengkal dan langkah memperebutkan identitas Hong Kong sebagai pusat keuangan global.
Namun, pemisahan etnis dalam pergerakan protes menghalau pemahaman yang lebih mendalam mengenai warisan kolonial dari perekonomi pekerja dan struktur institusional kota. Hal ini umumnya membuat para wanita buruh migran domestik dari Asia Tenggara yang menanggung dampak dari proses dekolonialisasi Hong Kong yang belum kunjung usai. Kota ini memiliki sejarah panjang mengenai praktek eksploitasi pekerja berbasis gender: contohnya, pada masa penjajahan, keluarga-keluarga kaya biasa bergantung pada ‘mui tsai’s, buruh domestik perempuan Cina yang dibayar sedikit bahkan tidak dibayar sama sekali.
Saat ini, para wanita diaspora yang berasal dari Asia Tenggara, keluar dari negara-negara asal mereka karena faktor ketimpangan gender dan ekonomi di daerah mereka, lalu memilih untuk melanjutkan bekerja sebagai perawat dasar. Cendekiawan Migrasi Rhacel Parreñas menjelaskan bahwa hal ini sebagai “pembagian kerja reproduksi internasional.” Ia menuangkan gagasan tersebut di dalam bukunya yang berjudul Servants of Globalization:
“Baik bagi kedua belah negara pengirim maupun penerima pekerja migran domestik, banyak wanita belum menerima pembagian kerja rumah tangga yang bersifat egaliter dan tidak bias dalam segi gender; namun, mereka telah menggunakan hak istimewa ras dan/atau kelas mereka untuk memindahkan peran reproduktif dengan tanggung jawab kepada para wanita yang tidak memiliki hak istimewa untuk melakukan hal tersebut.”
Untuk menggarisbawahi tuntutan buruh bukan menjadi masalah yang rumit bagi pemerintahan Cina yang otoriter. Sebaliknya, hal tersebut memacu kita untuk melihat kondisi perburuhan dalam segala dinamika kompleksitasnya—di dalam maupun di luar situasi pasca kolonialisme di Hong Kong.
Walaupun fakta di lapangan mengatakan bahwa jaringan migran dan transnasional telah membentuk identitas budaya kota, sebuah ide yang tidak kritis dan bersifat eksklusif dalam sebuah kepemilikan terus memperkuat perbedaan ras. Pergerakan radikal yang benar-benar dapat menentang ketidakadilan di Hong Kong harus tetap maju melebihi tuntutan untuk hak memilih secara universal dan adil, dan membangun jaringan antara kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan.
Untuk menggarisbawahi tuntutan buruh bukan menjadi masalah yang rumit bagi pemerintahan Cina yang otoriter. Sebaliknya, hal tersebut memacu kita untuk melihat kondisi perburuhan dalam segala dinamika kompleksitasnya—di dalam maupun di luar situasi pasca kolonialisme di Hong Kong. Mengapa upah sangat rendah untuk pekerja wanita Asia Tenggara, dan bahkan lebih rendah di negara asal mereka? Bagaimana pemerintah Hong Kong dan Cina terlibat atau secara aktif memfasilitasi jaringan ini? Seberapa mudah akses aksi demo bagi kaum minoritas yang terpinggirkan? Ini merupakan pertanyaan yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan oleh peserta aksi demo jika mereka ingin kebebasan dan demokrasi untuk seluruh warga Hong Kong.
Persatuan dan organisasi pekerja migran telah memainkan peran penting dalam isu yang mendasar dan penting ini. Namun ketika mereka telah mendapatkan apa yang mereka perjuangkan sepanjang tahun, mereka belum bisa mengerahkan pergerakan massa dalam solidaritas melawan globalisasi yang bersifat neoliberal. Tuntutan mereka untuk membuat protes kali ini agar lebih inklusif mendapat banyak tantangan dari pergerakan. Dalam petisi yang diselenggarakan sendiri oleh persatuan ibu rumah tangga sebagai wujud dukungan pada protes, menyarankan agar menjadikan buruh domestik tidak hanya sebagai pekerjaan yang sah, tetapi juga sebagai bentuk perjuangan luas akan kondisi di Hong Kong.
Migran, walaupun partisipasi mereka terbatas, memainkan peran yang penting dalam perekonomian dan aksi demo: pekerjaan mereka memungkinkan banyak keluarga untuk terlibat dalam aksi demo.
Siapa saja yang menambahkan kata 自己 (‘diriku’) pada yel-yel peserta aksi demonstrasi: 自己香港自己救 (“Kita sendiri yang akan menyelamatkan Hong Kong”)? Apa yang terjadi pada kegiatan aktivis dan analisis kita ketika beberapa dari 自己 (diriku) termasuk warga diaspora transnasional yang tinggal dan hidup membaur bersama seperti warga lokal lainnya? Pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan akademik dan spekulatif, namun mereka juga menentukan batasan konkret dari perjuangan pembebasan Hong Kong.
Melawan seluruh jenis penindasan di Hong Kong di bawah pemerintah kapitalis dan otoriter Cina juga perlu membongkar pola pikir chauvinis Han, etnonasionalisme Hong Kong, dan ideologi-ideologi yang bersifat eksklusif. Dan untuk melawan ambisi penjajahan Cina, kita harus melihat ke dalam: kebebasan tidak hanya terletak pada orang-orang yang berlindung di balik topeng hitam, namun juga pada semua yang tidak hadir di garis depan. Kita perlu berpikir kembali mengenai siapa saja yang termasuk pada warga lokal; dan bagaimana warga lokal berhubungan dengan warga transnasional lainnya. Untuk Hong Kong, sebuah penghubung untuk dunia, perlawanan akar rumput terhadap kapitalisme, yaitu pekerja migran di Hong Kong.
*Nama-nama di atas sudah diubah untuk melindungi identitas narasumber.