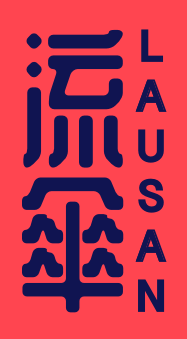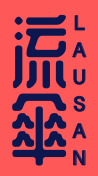Penerjemah: Nadia Damayanti
Diterjemahkan oleh sukarelawan dari komunitasi kami. Hubungi tim penerjemah untuk informasi lebih lanjut.
WY adalah seorang psikolog klinis dan anggota dari Hong Kong Demokratis oleh Aliansi Mahasiswa Pascasarjana Luar Negeri (AMPLN). Beliau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Harry Wu Yi-Jui (HKU) atas komentarnya pada edisi awal artikel ini. Versi berbahasa Cina dari artikel ini pertama kali diterbitkan di Apple Daily.
Masyarakat Hong Kong telah menjalani pergolakan dan transformasi yang luar biasa sejak aksi demo yang dilakukan oleh jutaan orang di bulan Juni melawan undang-undang ekstradisi, dan sedikit dari warga yang tinggal di kota yang tidak tersentuh dampak dari aksi demo, gas air mata di setiap distrik di Hong Kong, baku hantam dengan polisi dan adegan-adegan kekerasan lainnya yang mewarnai demonstrasi. Walaupun pergerakan demo telah menyatukan grup dari berbagai umur, kelas, etnis, politik, dan agama, hal tersebut juga menimbulkan konflik dari keluarga-keluarga dengan kondisi polarisasi yang membuat masyarakat menjadi sebuah mayoritas pendukung dengan skala besar dan minoritas orang tua menjadi oposisi dari aksi demo. Melihat kelanjutan pemerintah dalam menggunakan aparat kepolisian untuk menekan perbedaan sosial, walaupun adanya kekalahan telak di pemilu Dewan Distrik, tetap saja, masih belum ada kejelasan akhir dalam konflik ini.
Pergerakan sosial dan pergolakan dalam skala dan dampak yang besar memicu emosi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, khususnya untuk pendukung pergerakan yang menghadapi penindasan institusional dan kekerasan polisi. Ketakutan, kegelisahan, kemarahan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan merupakan respon alamiah terhadap hilangnya kepercayaan pada institusi kita dalam memberikan keamanan pribadi dan memberikan rasa adil; mereka semua yang melawan secara anonim di barisan depan, dengan segala bentuk resiko cedera dan ditangkap polisi dan seringnya mereka melawan tanpa dukungan keluarga mereka. Mereka adalah golongan rentan karena situasi mereka terpapar hal-hal yang membuat mereka trauma.

Trauma kolektif
Ini bukan sebuah istilah yang meremehkan situasi yang sedang dialami Hong Kong yaitu “trauma kolektif”— kejadian yang memicu trauma yang ditujukan dan menimpa seluruh grup dan komunitas. Lebih dari sekedar diagnosa label dari depresi, kegelisahan, atau gangguan stress pasca trauma, “trauma kolektif” menggarisbawahi hubungan tak terpisahkan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara, penindasan sosio-politis, dan luka psikologis yang disebabkan oleh pemerintah Hong Kong. Namun, yang terpenting adalah dengan mendefinisikan luka yang sama dan dipicu oleh sistem yang sama pada sebuah komunitas, mengizinkan kita untuk mengaitkan persamaan yang ada dalam solidaritas dan membuka kemungkinan untuk membangun solusi bersama untuk penyembuhan.
Ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, ketidakberdayaan, dan kesedihan merupakan respon alamiah yang muncul ketika runtuhnya kepercayaan terhadap institusi kita sebagai bentuk jaminan atas keselamatan dan pribadi dan penegakan hukum.
Melalui demo anti-ekstradisi, masyarakat telah menyingkirkan paradigma kuno dengan membentuk cara-cara baru untuk merevolusi dan menghidupkan pergerakan bersama-sama. Terinspirasi dari ide “kita semua mendaki bukit dengan cara kita sendiri,” “not cutting the mat”, merujuk pada slogan demo di Hong Kong yang berarti tidak memisahkan diri dari bagian pergerakan, “jadilah air” dan melalui cara kepemimpinan tanpa pemimpin dalam kutipan “revolusi di zaman kita.” telah memunculkan demonstrasi yang bersifat saling membantu satu sama lain antara masyarakat radikal dan pencinta damai, tua dan muda, dan dari seluruh elemen pekerjaan di masyarakat—pengacara, pekerja konstruksi, pekerja medis, pekerja sosial, ibu rumah tangga, guru, ahli finansial, dan berbagai macam pekerjaan. Hal ini juga memicu perubahan di dalam profesi mereka mengenai keterlibatan mereka dalam struktur yang menindas dan tidak manusiawi. Pemerintah telah memberikan senjata pada sistem hukum, medis, dan layanan sosial untuk menentang organisasi aktivis demonstran kedokteran, psikolog, dan pekerja sosial yang berasal dari Umbrella Movement, klinik-klinik kesehatan di bawah tanah dan layanan konseling Telegram memobilisasi untuk mengikuti wacana resmi dari pemerintah. Seruan para pekerja sosial mendesak, “Jangan jadi alat untuk ‘menjaga stabilitas’!”

Kesehatan jiwa lebih dari sekedar penyakit individu
Namun revolusi wajib berjalan sesuai dengan bagaimana kita mengkonseptualisasi peran kita dalam teori dan paradigma yang kita gunakan. Di dalam profesi yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, perhatian muncul ketika banyaknya peristiwa bunuh diri yang berkaitan dengan situasi politik. Para ahli memperingatkan adanya sebuah “epidemik” dari gangguan jiwa yang ditimbulkan dari kegiatan demo, dengan mengutip survei yang menunjukkan tingginya tingkat depresi, bahkan, mereka memberikan saran untuk menghindari menonton berita. Ini secara tepat dikritik sebagai perspektif yang tidak tepat yang mem-patologiskan reaksi penderitaan normal terhadap situasi yang tidak normal dan melucuti penderita dari konteks sosio-politik mereka. Seorang anak muda di Hong Kong tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari apa yang terjadi sama seperti seekor ikan dapat menyingkir dari kolam.
“Gangguan” jiwa telah lama didefinisikan dalam kehidupan sosial bahwa kondisi tersebut jauh dari kondisi “normal” oleh orang-orang yang berkuasa, seperti sejarah homoseksual digambarkan dengan diagnosa berdasarkan ras dan jenis kelamin. Bagaimana kita bisa mulai memahami arti “gangguan kejiwaan” ketika ancaman kekerasan dan dipenjara selalu ada dan adanya batasan yang terpisah di tatanan sosial? Bagaimana kita mendefinisikan “normalitas” di bawah kondisi yang ekstrim? Pakar psikolog pembebasan Martín-Baró menulis, “bereaksi terhadap [trauma kolektif] dengan kegelisahan yang tidak dapat dikontrol atau dengan sebentuk autisme harus dianggap sebagai reaksi normal pada keadaan yang abnormal, mungkin hanya hal tersebut yang dapat membuat seseorang berpegang teguh pada kehidupan dan bertahan dalam ikatan sosial yang menyesakkan dada.”. Keadaan mahasiswa yang melakukan demo di PolyU setelah seminggu dikepung polisi bertujuan sebagai gema yang mengganggu dari kejadian ini. Dalam “batas situasi” seperti itulah ketidakmampuan melihat penderitaan manusia sebagai penyakit individual menjadi semakin jelas.
Secara diam-diam, dengan menempatkan patologi tersebut pada penderita, struktur yang menindas — kekerasan yang terjadi di dalam negara, pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksetaraan, dan kondisi kehidupan yang buruk, masa depan Hong Kong yang suram — yang menyebabkan keputusasaan dan kegelisahan sedemikian banyak di antara kita menghilang dari pandangan, digantikan oleh tanggung jawab ganda atas orang yang entah bagaimana “memperbaiki diri” dengan mencari bantuan dari dokter, minum obat, mempraktikkan perawatan diri, menghindari berita; serta stigma sosial yang kuat yang melekat pada label “sakit jiwa.”. Definisi individu tentang “kesehatan mental” ini – pada dasarnya, menjadi “fungsional” dan konten dalam masyarakat yang terdistorsi dan bersifat traumatis – mengasingkan kita dari orang lain yang menderita dalam posisi yang sama. Stigma membuat kita merasa malu, dan ke arah solusi pil dan konseling individual yang berjuang untuk menjelaskan penderitaan kita.
Stigma membuat kita merasa malu, dan ke arah solusi pil dan konseling individual yang berjuang untuk menjelaskan penderitaan kita.
Jika pekerja kesehatan jiwa berkomitmen pada keadilan, kesembuhan, dan mulai memahami apa yang masyarakat perlukan, mereka harus menentang ideologi profesi mereka untuk membangun tatanan dan menolak menjadi alat negara dengan menyebarkan wacana yang tidak kritis kepada orang-orang yang mereka dukung. Dan apabila kita semua telah mengorientasi ulang tentang pemahaman bersama mengenai kesehatan jiwa dalam ranah sosial dan politik, maka akan menjadi jelas bahwa “penyembuhan” wajib mengatasi gejalanya yang bermanifestasi pada penderitaan seseorang, namun sebab dasar dari ketidakadilan sosial dan struktur yang tidak manusiawi.