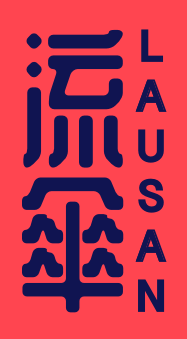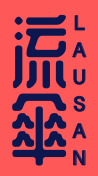Terbit pertama kali di 闹清楚 naoqingchu. Dipublikasikan ulang dengan izin. Wawancara ini telah disunting agar lebih padat dan jelas.
Penerjemah: Ellena
Diterjemahkan oleh sukarelawan di komunitas kami. Hubungi tim penerjemah untuk informasi lebih lanjut. Baca wawancara dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina.
Pada 1 Maret 2002, pekerja migran domestik asal Indonesia, sekaligus penulis dan jurnalis bernama Yuli Riswati berbincang dengan Ralf Ruckus dan Alina Kornfeldt tentang keterlibatan yang kelihatan dan tak kasat dari para pekerja migran domestik dalam perjuangan Hong Kong. Walau kerja-kerja mereka telah menopang gerakan—belum lagi fungsi mereka dalam hidup sehari-hari—kepentingan mereka terabaikan dalam tuntutan demokrasi Hong Kong.

Mempekerjakan pekerja domestik mungkin menjadi simbol status di banyak kota, tetapi di Hong Kong, seringkali merupakan kebutuhan dan bukan kemewahan. Satu dari delapan keluarga dan satu dari tiga keluarga dengan anak-anak mempekerjakan pekerja domestik untuk mengurus kebutuhan rumah tangga muda, lansia, dan sehari-hari. Sebagian besar rumah tangga bergantung pada pendapatan ganda untuk mampu biaya hidup mereka; lagi pula, Hong Kong adalah kota paling mahal di dunia untuk menyewa apartemen. Pekerja Hong Kong sudah memiliki hari kerja yang terkenal panjang, tetapi ada juga kurangnya fasilitas perawatan yang terjangkau untuk anak-anak dan orang tua. Untuk keluarga kelas pekerja, mempekerjakan pekerja migran domestik seringkali merupakan solusi paling ekonomis untuk kebutuhan perawatan mereka. Pekerja migran domestik memastikan majikan mereka dapat pergi bekerja dengan pakaian bersih dan rapi, menjaga rumah mereka aman dan terawat, merawat anak-anak mereka dan orang tua lanjut usia. Dengan kata lain, mereka terus memindahkan kehidupan di Hong Kong.
Baik peraturan imigrasi maupun kebijakan perburuhan Hong Kong memang telah lama mengingkari pentingnya peran para pekerja migran domestik. Pada tahun 1970-an, pemerintah Hong Kong memperkenalkan skema visa yang dengan efektif melegalkan kondisi kerja dan kehidupan yang eksploitatif bagi para pekerja migran domestik. Skema ini mengarahkan para pekerja migran domestik untuk tinggal bersama pemberi kerja mereka, serta mengecualikan sistem gaji mereka—yakni yang tadinya merujuk upah minimum sesuai undang-undang menjadi gaji bulanan yang konstan. Mereka berhak mendapatkan satu hari libur setiap minggunya, tapi jam kerja mereka tidak diatur. Visa mereka sangat bergantung pada si pemberi kerja, dan jika si pekerja diragukan atau jika pemberi kerja mereka memutus kontrak, maka si pekerja diwajibkan untuk mendapat pemberi kerja baru dalam waktu dua minggu atau mereka akan dideportasi.
Di Hong Kong, ada 150.000 orang PRT asal Indonesia. Mereka adalah kelompok pekerja migran domestik terbesar kedua di sana. Mereka mengorganisir diri, menggelar demonstrasi dan protes, serta melayangkan tuntutan pada pemerintah Hong Kong dan Indonesia. Pemerintah Indonesia, bagaimanapun juga, membatasi partisipasi politik para pekerja migran domestik. Indonesia sangat bergantung pada uang yang dikirim oleh para TKI dari luar negeri. Faktanya, kiriman uang ini telah menjadi sumber pendapatan luar negeri terbesar kedua Indonesia setelah ekspor minyak dan gas bumi.
Pada Juni 2019, penyusunan undang-undang ekstradisi telah memicu protes besar yang didukung oleh mayoritas masyarakat Hong Kong. Yuli Riswati mengamati dan melaporkan protes ini sepanjang Juni hingga Oktober 2019. Sejak 2017, ia telah menawarkan berbagai pendampingan pada sesama pekerja migran domestik melalui media sosial. Pada Maret 2019, ia meluncurkan Migran Pos, sebuah kanal berita non-profit yang memublikasikan berita penting terkini untuk komunitas Indonesia. Selama masa pergerakan Hong Kong, para pekerja migran domestik menjadikan Migran Pos sebagai rujukan terpercaya dalam mencari informasi mengenai protes yang berlangsung.
Awal bulan Desember 2019, Yuli dideportasi oleh kantor imigrasi Hong Kong dengan tuduhan melanggar izin tinggal. Dia ditangkap di flatnya pada bulan September, kemudian ditahan selama 28 hari di bulan November. Selama ditahan, ia mengalami perlakukan yang tidak manusiawi. Begitu ia dideportasi, sejumlah kelompok di Hong Kong mengorganisir aksi solidaritas yang sekaligus memprotes kondisi para tahanan di rutan-rutan Hong Kong.
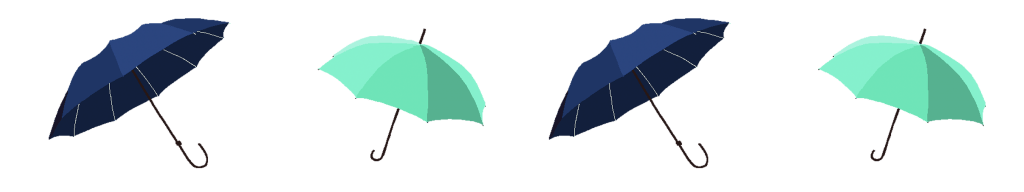
Dukungan tak kasat mata
Ralf Ruckus/Alina Kornfeldt: Seperti apa keterlibatan para pekerja migran domestik dalam protes yang berlangsung?
Yuli Riswati: Para pekerja migran domestik yang mengerti demokrasi mendukung protes-protes yang berlangsung, tapi mereka tidak berpartisipasi secara terbuka dalam gerakan karena risikonya terlalu tinggi. Mereka takut partisipasi mereka dalam gerakan akan berujung pada diskriminasi, deportasi, hingga larangan bekerja di Hong Kong. Mayoritas pekerja migran domestik tidak punya pemahaman mendalam mengenai politik maupun apa yang sedang terjadi di Hong Kong.
Saya ngobrol dengan para pekerja migran yang berkontribusi dalam gerakan sepanjang hari kerja mereka untuk memastikan kesehatan para majikan yang bergabung dalam aksi. Para pekerja migran ini menyiapkan makanan yang mereka bawa ke titik demonstrasi, membawakan peralatan seperti payung untuk menghindari pengambilan foto dan peluru karet. Mereka mengingatkan majikan mereka beserta keluarganya untuk membawa masker serta baju ganti setiap akan berangkat aksi. Salah satu contohnya seorang pekerja migran domestik yang saya jumpai di pasar. Ia membawa lima hingga enam payung sekaligus.
Saya tanya ke dia, “Kamu beli payung? Kok banyak sekali?”
Dia menjawab, “Iya, saya beli untuk majikan saya. Kita kehabisan payung di rumah.”
“Masa? Kok mereka bisa kehabisan payung?”
“Mereka perlu bawa payung untuk ikut aksi. Saya belikan payung-payung ini untuk mereka: untuk majikan saya dan anak-anaknya.”
“Mereka semua ikut demonstrasi?”
“Iya, majikan saya yang laki-laki ikut. Anak perempuannya juga, bareng dengan dua anaknya. Mereka semua turun ke jalan dan masing-masing mereka perlu bawa payung. Jadi, saya belikan untuk mereka.” Dia menambahkan, “Penjaga toko sampai bertanya, kenapa saya beli banyak payung. Ia lelaki tua yang pro-pemerintah. Saya bilang saja kalau saya mau mengirimkan payung-payung ini ke kampung halaman karena payung di Hong Kong lebih bagus kualitasnya.”
Sebagian kecil pekerja migran ikut terlibat langsung dalam aksi, dengan kapasitas mereka sebagai PRT. Seorang pekerja bercerita tentang majikannya yang berusia 70 tahun. Ia mau mendukung para anak-anak muda yang turun ke jalan, tapi ia tidak punya siapa-siapa untuk diajak karena suaminya sakit-sakitan dan harus jalan pakai tongkat.
Dia bilang ke PRT-nya, “Saya mau ikut dalam aksi, tapi saya tidak bisa berangkat dengan suami saya karena ia sulit berjalan. Ikut bareng dengan putra saya juga tidak mungkin, karena dia pasti ada di garda depan. Ia harus lari kalau peserta aksi bentrok dengan polisi.”
Si PRT ini kemudian menjawab, “Kalau butuh teman, saya bisa menemani.”
“Tapi, itu berarti kamu jadi tidak bisa libur.”
“Saya tidak keberatan kok. Yang penting Ibu bahagia. Selama ini Ibu baik sama saya.”
Maka, PRT ini kemudian menemani majikannya setiap kali ia ikut aksi. Ia mengorbankan hari liburnya, sebab majikannya juga baik padanya (tentu saja, dia dapat kompensasi karena kerja di hari libur). Keduanya saling pengertian. Si pekerja membawakan makanan dan minuman untuk majikannya yang sudah lanjut usia dan tidak bisa bawa bawaan berat. Ia memastikan agar majikannya bisa menjangkau arena demonstrasi lalu pulang dengan selamat. Mereka harus berjalan jauh sekali. Saat majikannya kelelahan, si PRT akan menawarkan majikannya untuk istirahat atau makan.
Saya bertanya pada pekerja ini, “Apakah kamu memang bermaksud untuk ikut serta dalam gerakan?”
“Ya, sebenarnya tidak. Yang penting adalah membantu majikan saya. Saya tahu bahwa ia sedang memperjuangkan banyak hal, maka saya mau menolongnya.”
Selain mendukung gerakan dengan memastikan kesehatan fisik majikan mereka, para pekerja migran domestik ini juga memberikan dukungan moral. Misalnya, mereka menghibur majikan mereka yang bertengkar dengan anak-anaknya yang ikut demonstrasi. Saya ngobrol dengan para pekerja yang majikannya mengusir anak-anak mereka dari rumah.
Para majikan ini berkata pada anak-anak mereka, “Kalau kamu sampai kena masalah, jangan bawa-bawa kami,” atau, “Kamu bukan anak kami lagi.”
Anak-anak muda ini tidak pulang ke rumah berbulan-bulan dan tidak mengabari orangtua mereka, namun mereka memastikan orangtuanya baik-baik saja lewat PRT mereka. Para pekerja ini diam-diam mengambil peran sebagai mediator, menjembatani komunikasi antara orangtua dan anak yang hubungannya renggang. Ketika anak-anak ini memilih untuk meninggalkan rumah, sebenarnya mereka tidak sampai hati untuk melakukannya.
Mereka pun menghubungi si PRT untuk menanyakan kabar orangtua mereka tanpa menghubungi orangtuanya secara langsung, “Bagaimana kabar mama? Dia rutin minum obat, kan? Jaga mama baik-baik ya.”
Pekerja ini pun terlibat secara emosional. Dukungan dan penghiburan yang ia berikan telah memungkinkan para demonstran untuk bisa fokus pada aksi tanpa harus khawatir tentang keluarga mereka di rumah.
Sebaliknya, para pemberi kerja juga meminta para PRT-nya untuk menjadi pembawa pesan bagi anak-anak mereka. Dalam satu kasus, terjadi konflik besar antara seorang ibu dengan putra-putranya sampai mereka tidak saling menyapa satu sama lain. Si ibu kadang membelikan putra-putranya makanan kesukaan mereka dengan mengirimkan makanan itu melalui PRT-nya.
“Tolong kasih ini ke gogo (kakak laki-laki) dan sailou (adik laki-laki). Pasti mereka tidak bisa makan ini sekarang.”
Kemudian, si PRT akan menghubungi anak-anak itu, “Kalian di mana sekarang? Saya mau bawakan sup.”
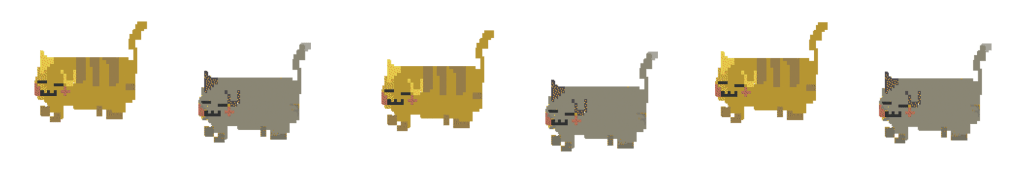
Pengucilan dalam gerakan
RR/AK: Menurutmu, apakah kontribusi pekerja migran domestik dalam gerakan ini cukup diapresiasi?
YR: Terlepas dari kontribusi yang diberikan, kami mengalami perlakukan yang tidak adil karena tidak punya akses informasi dan perlindungan yang memadai. Awalnya, baik pemerintah maupun warga Hong Kong tidak menganggap bahwa kami ini juga bagian dari mereka, dan karenanya kami juga butuh terinformasi tentang apa yang sedang terjadi.
Padahal, faktanya, tanpa disadari, pekerja migran domestik telah ikut terlibat dalam gerakan. Bukan tidak mungkin para pekerja ini terluka akibat peluru karet atau terpapar gas air mata saat berada di luar rumah. Namun, kontrak kami menyebutkan kalau asuransi kesehatan kami tidak bisa menanggung perawatan untuk cedera yang kami alami selama hari libur. Jadi, menggunakan hak atas hari libur kami dengan menghabiskan waktu di luar rumah punya risiko yang besar. Siapa yang menjamin keselamatan kami? Jika kami tidak terlindungi, ini artinya hak kami untuk menikmati rehat sehari dalam seminggu telah dirampas, baik karena kami terlibat dalam gerakan secara langsung maupun tidak.
Pemerintah Hong Kong, pemerintah Indonesia, maupun orang Hong Kong tidak merasa bahwa kami bisa punya pandangan politik sendiri. Karenanya, mereka tidak melibatkan kami. Kenapa kami selalu diperlakukan seperti anak-anak, didikte bagaimana harus bersikap dan tingkah laku apa yang boleh kami kembangkan? Jika kami punya akses lebih banyak terhadap informasi, kami bisa mengembangkan pandangan kami sendiri terhadap gerakan. Bagaimana kami merespon gerakan seharusnya menjadi pilihan kami sendiri sebagai orang dewasa. Kami diharapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan mematuhi semua pendapat dan pilihan orang lain, kami tidak pernah dibiarkan untuk bicara atau mengambil pilihan untuk kami sendiri. Mereka benar-benar mendiskriminasi kami dengan perlakuan semacam ini.
Namun, sejauh ini, kami dihalangi untuk bisa bersikap dan menyuarakan aspirasi, seakan-akan kami berbeda dengan para penduduk lokal, atau orang Hong Kong, atau apapun lah kamu menyebut mereka. Bagi saya, pertanyaannya kemudian adalah: siapa yang seharusnya disebut sebagai orang Hong Kong?
Mereka yang saya maksud adalah pemerintah Hong Kong, para penduduk lokal, pemerintah Indonesia, dan bahkan sebagian besar dari komunitas kami sendiri. Bahkan, beberapa dari kami telah menginternalisasi diskriminasi ini: kita ini cuma perempuan dan tugas kita hanya mengerjakan tugas-tugas domestik, mematuhi majikan, dan mendengarkan instruksi pemerintah. Ketika ada yang berani punya pendapat berbeda, mereka akan menganggap orang itu telah membahayakan komunitas lantas menggertaknya hingga ia pasrah, lantas tak lagi memperlakukannya sebagai bagian dari kami.
Menurut saya, semua orang harus sadar bahwa pekerja migran setara derajatnya dengan semua orang di Hong Kong. Terlepas dari status legalnya, pekerja migran domestik juga manusia seperti yang lain, sama-sama orang dewasa yang bisa mengambil keputusan sendiri, dan mampu membentuk pandangan mereka sendiri terhadap gerakan yang ada. Namun, sejauh ini, kami dihalangi untuk bisa bersikap dan menyuarakan aspirasi, seakan-akan kami berbeda dengan para penduduk lokal, atau orang Hong Kong, atau apapun lah kamu menyebut mereka. Bagi saya, pertanyaannya kemudian adalah: siapa yang seharusnya disebut sebagai orang Hong Kong? Kami terlibat dengan berbagai cara, secara sukarela maupun dengan paksaan, karena pekerjaan kami atau karena pilihan kami sendiri. Pada akhirnya, mau disebut sebagai orang Hong Kong atau bukan, kami adalah bagian dari Hong Kong.
RR/AK: Ketika kamu mengumpulkan informasi dan mengambil foto selama demonstrasi, reaksi macam apa yang kamu temui?
YR: Kadang saya dicurigai karena penampilan saya yang cukup menonjol. Saya memakai hijab dan pakaian saya berbeda dengan para demonstran.
Suatu kali, saya mengambil foto di antara sejumlah jurnalis. Tiba-tiba ada yang mendekati saya dan bertanya, “Apakah kamu jurnalis?”
Saya menunjukkan kartu pers yang saya punya dari Migran Pos. Itu cukup baginya, “Oke. Kalau kamu memang jurnalis, saya tidak akan mengganggu kamu.”
Dalam kesempatan lain, ketika saya mengambil foto, beberapa perempuan berseru, “Hei, kamu gak boleh sembarangan ambil foto.” Tiba-tiba mereka semua mulai mencerca saya.
Saya menjelaskan, “Saya paham. Saya tidak mengambil foto yang menampakkan muka. Saya sadar foto apa yang boleh dan tidak boleh saya ambil.” Lantas, saya menunjukkan kamera saya pada mereka.
Saya dicurigai berkali-kali karena saya tampak berbeda. Saya pikir, ada semacam bias, bahwa mereka menganggap saya tidak setara dengan mereka, bahwa mereka merasa terganggu dengan kehadiran orang yang begitu berbeda dari mereka tapi ada di tengah-tengah protes bersama mereka.
Saya mengalami penolakan bukan hanya dari peserta aksi pro-demonstrasi tapi juga dari para pendukung pemerintah. Suatu kali, saya sedang mengumpulkan informasi tentang protes di Admiralty, sebuah distrik bisnis di Hong Kong. Seorang perempuan lanjut usia lantas mendatangi saya, “Ngapain kamu foto-fotoin polisi? Mereka kan lagi bertugas.” Ia kemudian memukul saya.
Saya bilang, “Kamu tidak boleh memukul saya.”
Banyak orang kemudian datang melindungi saya. “Kamu tidak boleh memukul dia. Kalau kamu pukul dia, kamu bisa dilaporkan ke polisi.”
Tentu saja tidak semua orang dalam gerakan menolak kami. Sebagian besar dari demonstran tidak keberatan dengan kehadiran kami. Para demonstran yang lebih muda bersikap lebih ramah lagi pada kami. Sebagian dari mereka sangat peduli. Saya sedang duduk bersama para demonstran di sebuah mal ketika polisi datang. Langsung ada yang membuka payung dan menutupi kepala saya. Saya menoleh.
Ia bilang, “Kamu harus pakai payung karena ada polisi di atas. Mereka sedang merekam kita. Saya gak mau kamu ikut terekam. Sebaiknya kamu pasang maskermu.”
Di waktu lain, saya sedang melaporkan sebuah protes di Sham Shui Po. Di stasiun metro, saya sedang mengambil gambar makanan dan pakaian ganti yang ditinggalkan para demonstran di mesin tiket. Tiba-tiba, nampak para demonstran berlarian.
Sebagian dari mereka berhenti dan berkata pada saya, “Jeje (kakak perempuan, panggilan pada pekerja migran domestik dalam bahasa Kanton), kamu harus meninggalkan tempat ini. Di sini berbahaya. Ayo ikut dengan kami, kami mau naik metro.” Saya begitu tergugah oleh para demonstran yang masih sempat melindungi kami ketika mereka sendiri sedang dalam bahaya.
Dalam kesempatan lain, saya menyaksikan seorang PRT yang terjebak di area protes. Ia menangis ketakutan.
Salah seorang demonstran muda bertanya, “Kamu kenapa?”
“Saya mau pulang. Rumah majikan saya di sebelah sana, tapi saya takut.”
Anak muda ini kemudian mencopot helmnya dan memasangkan helm itu di kepala si PRT, sementara seorang temannya melindungi si PRT dengan payung. Dua demonstran ini kemudian menemani si PRT melalui area yang padat. Saya begitu kehilangan kata-kata menyaksikan ini. Saya bahkan tidak bisa memotret karena tergugah. Mereka peduli pada kami ketika kami butuh perlindungan, meskipun kami tidak terlibat secara langsung dalam gerakan.
Beberapa pengunjuk rasa juga akan berkata kepada pekerja migran domestik, “Maaf, jeje, kita harus lewat di sini. Maaf menggangu Anda.”

Ketimpangan keadilan dan partisipasi
RR/AK: Dari sudut pandangmu sebagai seorang pekerja migran domestik, apa yang seharusnya ditambahkan ke dalam Lima Tuntutan?
YR: Pekerja migran domestik tidak terwakilkan dalam Lima Tuntutan ini, namun undang-undang ekstradisi juga akan berdampak pada kami karena akan mengatur semua orang yang ada di Hong Kong. Tuntutan atas hak pilih, misalnya, tidak akan berdampak pada kami karena kami bukan warga negara Hong Kong. Saya tidak tahu apa saya berhak mengatakan ini, tapi jika boleh menambahkan, perlu ada tuntutan yang mewakili hak para pekerja migran domestik serta minoritas etnis di Hong Kong. Itu berarti, hentikan diskriminasi dan berikan keadilan akses terhadap informasi.
Ada ketimpangan antara warga negara Hong Kong, minoritas etnis, dan pekerja migran domestik. Diskriminasi dan rasisme menjadi realita kehidupan kami sehari-hari. Memenuhi tuntutan atas perlakuan yang adil bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Ini juga tanggung jawab warga negara Hong Kong. Kami mendukung perjuangan mereka karena kami merasa bahwa kami juga bagian dari masyarakat Hong Kong, bahkan ketika tuntutan mereka tidak mengikutsertakan kami. Kami bersolidaritas sebab kami tahu bahwa jika orang Hong Kong kehilangan kebebasan ekspresi mereka, maka kami juga akan kehilangan kebebasan kami.
Saya pikir, sebuah gerakan yang mengikutsertakan minoritas etnis dan pekerja migran domestik dari akar rumput akan melampaui jurang antara tuntutan terhadap keadilan, diskriminasi terhadap yang non-warga negara, serta ketidakpedulian terhadap orang-orang yang sebenarnya tinggal bersama mereka yang turun ke jalan.
Menurut saya, apapun yang jadi tujuannya, gerakan ini akan jadi makin kuat jika mempertanyakan persoalan pengucilan. Slogan “kita terhubung”, yang pertama kali muncul pada Oktober 2019 akibat konflik yang berdampak pada minoritas etnis, memicu pertanyaan lebih luas akan relasi minoritas etnis di Hong Kong. Rumor yang beredar telah mengkambinghitamkan sejumlah masyarakat Asia Tenggara atas serangan terhadap aktivis pro-demokrasi. Baik komunitas Muslim dan non-Muslim sama-sama khawatir ketika polisi menembakkan water cannon hingga meledakkan masjid terbesar di Hong Kong dengan cat biru menyengat saat membubarkan massa.
Saya pikir, sebuah gerakan yang mengikutsertakan minoritas etnis dan pekerja migran domestik dari akar rumput akan melampaui jurang antara tuntutan terhadap keadilan, diskriminasi terhadap yang non-warga negara, serta ketidakpedulian terhadap orang-orang yang sebenarnya tinggal bersama mereka yang turun ke jalan. Kalau kamu mau gerakanmu berhasil, jangan mengabaikan para pekerja migran domestik yang ikut berkontribusi terhadap kegigihan gerakan. Kami mengurusi semua hal di rumahmu dan memastikan keluargamu sehat-sehat. Jangan lupa bahwa kami bisa saja bilang kalau ini bukan pekerjaan kami: tugas kami hanya membereskan urusan domestik, bukan membangun ikatan emosional denganmu. Namun faktanya, kamu butuh lebih dari urusan domestik. Inilah kenapa orang Hong Kong harus melibatkan kami dan minoritas etnis lainnya. Mereka harus berhenti menganggap bahwa hanya merekalah yang paling tahu soal Hong Kong.
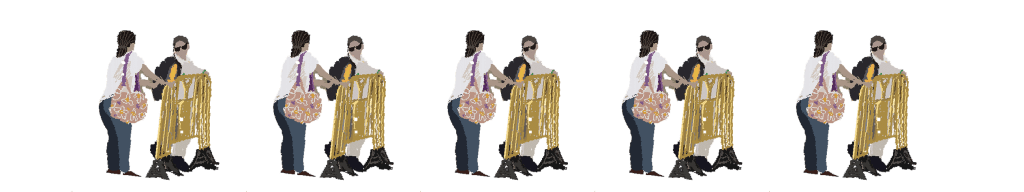
Kesamaan perjuangan antara Hong Kong dan Indonesia
RR/AK: September dan Oktober tahun lalu, terjadi protes besar di Indonesia akibat rancang perundangan yang akan menggembosi kekuatan KPK, kebebasan berekspresi, membatasi kebebasan personal, dan menghancurkan lingkungan hidup. Bagaimana protes ini berkaitan dengan protes di Hong Kong?
YR: Gerakan besar di Hong Kong telah menginspirasi protes di Indonesia. Sejak protes 1998 dan kejatuhan rezim Soeharto, belum pernah ada lagi protes besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Nampaknya orang Indonesia telah merasa nyaman dengan masa reformasi, yakni masa transisi yang terjadi selepas pengunduran diri presiden otoriter Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.
Sebenarnya, ada banyak persoalan yang membuat orang Indonesia kecewa. Mereka telah menunggu waktu untuk melantangkan suara mereka. Apa yang terjadi di Hong Kong menginspirasi teman-teman di Indonesia dan memberikan mereka motivasi: “Di Hong Kong, anak-anak muda sudah turun ke jalan.” Namun, gerakan Hong Kong juga terinspirasi oleh gerakan di Indonesia. Mereka melihat ada kesamaan antara Soeharto dan Carrie Lam. Kedua pemimpin ini menolak untuk turun jabatan dan siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Pada 1 Juli, demonstran di Hong Kong menyerbu Dewan Legislatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Beberapa mencuit bahwa mereka terinspirasi oleh gerakan 1998, ketika para demonstran menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta dan berujung pada berakhirnya kekuasaan otokratis Soeharto.
Apa yang terjadi di Hong Kong menginspirasi teman-teman di Indonesia dan memberikan mereka motivasi. Namun, gerakan Hong Kong juga terinspirasi oleh gerakan di Indonesia.
Dari bom molotov sampai pembakaran ban, kedua gerakan ini saling menginspirasi satu sama lain dalam hal taktik. Mereka sama-sama berjuang melawan tirani dan menuntut demokrasi.
Pada September 2019, ketika orang-orang menjalankan protes terhadap pemerintah di Jakarta, tagar “Reformasi Dikorupsi” (gerakan reformasi telah dikorupsi) mulai muncul di Hong Kong. Saya pernah mengambil foto sebuah graffiti bertuliskan “reformasi dikorupsi”. Saya yakin bahwa orang Hong Kong yang tidak bisa berbahasa Indonesia, atau orang non-Indonesia, yang membuat graffiti tersebut karena penulisannya salah dan ada teks yang dicoret.
Saya juga pernah mendengar percakapan di antara para demonstran, “Sayang sekali apa yang terjadi di Indonesia. Beberapa orang ditembak. Mereka mati.” Mereka merasakan adanya keterhubungan atas apa yang terjadi di Indonesia dengan represi yang mereka hadapi di Hong Kong.
Mereka peduli pada teman-teman di Indonesia, dan yang di Indonesia peduli pada teman-teman di Hong Kong. Keduanya menghadapi kekerasan dan kesewenang-wenangan dari pemerintahan yang korup dan polisi yang ganas. Ikatan emosional muncul dari kedua gerakan walau mereka tidak langsung terhubung satu sama lain. Walau belum ada gerakan solidaritas yang terang-terangan untuk Hong Kong di Indonesia, saya pernah melihat pesan solidaritas untuk Indonesia di Hong Kong: “Kami bersama Indonesia.”
Saya pernah ketemu seorang demonstran yang bilang kalau dia merasa simpatik atas penindasan yang dialami teman-teman Indonesia di bawah pemerintahan yang inkompeten.
“Bagaimana kamu tahu soal Indonesia?”
“Aku membaca banyak hal, jeje. Aku mempelajari sejarah Indonesia. Sekarang kita bisa mencari semua informasi ini di internet. Aku juga baca sejarah kejatuhan Soeharto.”
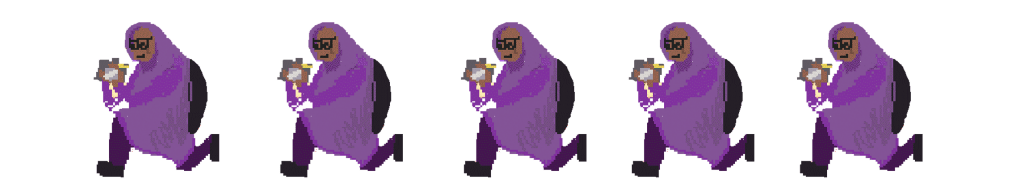
Solidaritas dengan pekerja migran domestik
RR/AK: Ketika kamu dideportasi, sejumlah aktivis di Hong Kong mengorganisir aksi solidaritas. Siapa yang mendukungmu?
YR: Di antara mereka adalah para penduduk setempat, jurnalis internasional, sejumlah individu lokal, pengungsi, dan orang-orang yang terlibat dalam persoalan pekerja migran, seperti anggota sejumlah kolektif, atau anggota Federasi Pekerja Domestik Asia Hong Kong. Beberapa dari mereka juga bagian dari Lensational, sebuah organisasi yang mendukung pekerja perempuan di tempat-tempat seperti Hong Kong, India, dan Pakistan dengan mengajarkan fotografi. Saya aktif menjadi murid dan tutor di sana.
Beberapa dari peserta aksi benar-benar mengejutkan saya. Seorang teman mengirimkan video berisi seorang anak berusia 12 tahun yang ikut aksi.
“Kenapa kamu ikut aksi solidaritas ini?”
“Aku mau dukung Yuli karena di rumahku juga ada jeje. Jeje begitu baik pada kami.”
“Lalu, kenapa kamu memakai masker?”
“Supaya tidak ketahuan orangtua. Mereka tidak mendukung demonstrasi ini.”
RR/AK: Bagaimana aksi Keadilan untuk Yuli berbeda dengan aksi solidaritas untuk pekerja migran domestik yang pernah ada sebelumnya, seperti aksi solidaritas untuk Erwiana, seorang PRT yang disiksa oleh majikan dan kasusnya memicu percakapan publik tentang pekerja migran di Hong Kong pada 2015?
YR: Aksi solidaritas Keadilan untuk Yuli mempertanyakan pengucilan pekerja migran domestik dari identitasnya sebagai orang Hong Kong. Para organisator punya ide untuk mengubah istilah “pekerja asing domestik”, yang umum digunakan di Hong Kong, menjadi “pekerja migran domestik”. Mereka mempertanyakan penyebutan pekerja migran domestik sebagai ‘orang asing’: “Bukankah tidak adil untuk menganggap mereka sebagai orang asing ketika sebenarnya mereka adalah bagian dari kita?” Aksi tersebut memicu percakapan di antara para pendukungnya: bagaimana seharusnya kita memperlakukan PRT?
Akibat aksi tersebut, gerakan solidaritas di Hong Kong pun jadi mulai ikut mengadvokasi hak para pengungsi dan tahanan di Pusat Imigrasi Castle Peak Bay (CIC) yang ditahan sebelum dideportasi. Untuk memastikan akses para tahanan terhadap keadilan, sejumlah orang dalam Kelompok Peduli Hak Tahanan CIC, contohnya, telah menentang pemerintah terkait klaim-klaim penahanan ilegal mereka. Kasus saya telah memperlihatkan banyak sekali perlakuan tidak adil di rutan, dan banyak eks-tahanan pun mulai ikut membagikan pengalaman mereka.
Kontribusi lainnya oleh Yuli Riswati
Afterwork (KUNCI & Parasite, 2016), sebuah antologi yang memuat cerpen yang ditulis oleh Yuli Riswati.
Pidato Yuli dalam demonstrasi Hari Perempuan Internasional di Berlin pada 8 Maret 2020.
Kontribusi Yuli pada pameran afterbefore: images and sounds from hong kong, sebuah pameran fotografi, video, seni suara, dan tulisan di The Gallery at Chinatown Soup, New York, 29 Januari – Februari 2020.