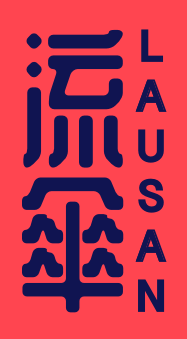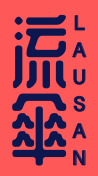Asli: Pertama kali diterbitkan di Good Men Project. Diterbitkan ulang dengan izin.
Penulis: R. Benedito Ferrão adalah Asisten Profesor Sastra Inggris dan Studi Asia & Kepulauan Pasifik Amerika di College of William and Mary, sekaligus penulis internasional.
Penerjemah: SR, Nadia Damayanti, Ellena
Diterjemahkan oleh sukarelawan dari komunitasi kami. Hubungi tim penerjemah untuk informasi lebih lanjut. Baca artikel dalam bahasa Inggris dan bahasa China.
Selama bertahun-tahun saya telah mendatangi ke kota pelabuhan ini, namun saya belum pernah melihatnya dalam kondisi seperti sekarang. Hong Kong dalam keadaan terkepung. Saya tiba pada 5 Agustus, pada hari pemogokan massal. Saya disambut oleh toko-toko yang tutup di Causeway Bay. Saat itu pukul 5 sore. Kota yang terkenal dengan daya tarik komersial dan aktivitas malamnya itu terlihat suram. Di Times Square, saya melihat beberapa laki-laki dan perempuan berpakaian hitam, semua memakai topeng hitam, beberapa mengenakan topi pelindung, dan yang lainnya membentangkan payung hitam walau hujan tidak turun, sebagai simbol protes. Saya langsung mengambil ponsel saya untuk mengambil foto.
Salah seorang anak muda berjalan menghampiri saya dan meminta saya bisa untuk tidak memotret wajah para pengunjuk rasa. Suaranya terdengar redam dari balik masker. Saya menunjukkan kepadanya foto yang saya ambil: payung menutupi semua bagian, kecuali beberapa pasang kaki di tengah cahaya yang memudar.
Saya tidak pernah melihat Hong Kong seperti ini.
Protes dipicu oleh kemunculan rencana undang-undang yang disodorkan oleh Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hong Kong, pada awal tahun ini. RUU ini akan mengekstradisi para pelaku kriminal untuk diadili di China. Pada bulan September, Lam menarik RUU tersebut. Namun, kekacauan sudah terjadi. Gerakan protes yang makin kuat terus mendesak reformasi demokrasi.
Pada tahun 2014, Revolusi Payung punya kemiripan tuntutan perubahan, dengan payung yang lagi-lagi berfungsi sebagai simbol protes. Gerakan tersebut berumur pendek; kali ini, payung-payung tersebut belum disingkirkan karena para demonstran justru terus mempertanyakan hubungan antara Hong Kong dan China—masalah yang tidak pernah sepenuhnya diselesaikan pada akhir kolonialisme Inggris di wilayah tersebut.
Hong Kong adalah salah satu kota asing pertama yang saya kunjungi sendiri begitu dewasa. Waktu itu, saya berusia 21 dan dalam perjalanan pertama itu saya bepergian antara California dan Goa untuk menjenguk keluarga yang bermigrasi ke Amerika Serikat.
Kenangan transit di Hong Kong akan selalu punya tempat istimewa dalam ingatan saya tentang perjalanan pendewasaan diri. Namun, ingatan itu hanya bagian kecil dari momentum sejarah yang lebih besar lagi. Saat itu, tahun 1995, hanya dalam waktu satu tahun, Hong Kong memasuki masa transisi dari Britania Raya—yang telah berkuasa di sana selama 99 tahun—ke China.
Transit berikutnya di Hong Kong memungkinkan saya untuk mengunjungi Makau. Saat itu tahun 1999, tahun ketika masa kontrak Portugal atas pulau tersebut akan berakhir, menyebabkan Makau turut menjadi bagian dari China. Penyerahan itu akan menutup setengah milenium kolonialisme Portugis di Asia, menjalar hingga ke tanah air saya sendiri. Goa, Estado da Índia, dikuasai oleh Portugis pada 1510 hingga 1961.
Saat itu, saya belum jadi orang pertama di keluarga saya yang mengunjungi sisa-sisa kerajaan Eropa di tanah Asia. Namun, sebelum kunjungan anggota keluarga saya ke daerah ini, pengaruh budaya pulau ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan kami.
Bagi saya, Hong Kong dan Macau selalu tampak mirip dengan sejarah Goa.
Dalam kunjungan solonya ke Hong Kong dan Makau beberapa tahun kemudian, ayah saya mengambil foto porselen biru dan putih yang mengingatkannya pada berbagai kerajinan keramik yang masih ada di rumah kakek-nenek saya, sebagaimana lazimnya ditemui di umah-rumah orang Goa lainnya.
Dunia Lusophone telah menghubungkan berbagai wilayah Asia, seperti Goa, Timor, dan Makau. Meski, sejumlah koneksi intra-Asia ini sebenarnya telah ada sebelum kedatangan Portugis.
Dalam perjalanan-perjalanan awal saya ke Hong Kong dan Makau, saya memperoleh nomor telepon teman-teman keluarga Goa saya yang tinggal kedua tempat itu. Tahun-tahun berikutnya, saya mempelajari para tokoh yang sejarah kekerabatannya mengandung bukti ikatan budaya antara wilayah-wilayah ini, di antaranya adalah Machado Tionghoa yang meninggal baru-baru ini. Machado ini lahir di tahun 1929 dan menjadi salah satu model pertama yang populer di kancah internasional dengan garis keturunan campuran Tionghoa, Goa, dan Portugis.
Dengan ikatan ini, bagi saya Hong Kong dan Makau secara historis tampak serupa dengan Goa Tempat-tempat kecil dengan jalinan ragam budaya yang kompleks, titik-titik ini menyerap dan mentransmutasikan berbagai pengaruh yang datang dari jauh, melokalkan dan menjadikannya budaya mereka. Ini bukan berarti segalanya baik-baik saja di pos-pos jajahan ini.
Perlawanan politik muncul dari banyak titik sepanjang sejarah tanah ini. Namun, pengetahuan lokal serta perkembangan budaya mereka sendiri telah digerogoti oleh momen-momen kontemporer dalam menceritakan sejarah, terutama di hadapan nasionalisme.
Tidak seperti di Hong Kong dan Makau, berakhirnya kekuasaan Eropa di Goa tidak datang dari sebuah kesepakatan. Perang dua-hari berakhir pada 19 Desember 1961, yakni ketika tentara India dengan cepat mengalahkan sekelompok kecil pasukan militer Portugis di Goa. Sementara ada sejumlah permutasi pandangan politik di antara masyarakat Goa tentang persoalan kolonialisme, termasuk faksi pro- dan anti-Portugis dan India, masyarakat Goa tidak diberi pilihan atas kemerdekaan tanah mereka sendiri.
Aneksasi India di Goa membatasi upaya pembebasan rakyat dan menjadikan bekas wilayah India-Portugis sebagai koloni dari sebuah wilayah pascakoloni. Ironi itu begitu jelas mengingat bahwa baru pada tahun 1947 India bisa menggulingkan penjajahan Inggris lewat penentuan nasib sendiri.
Dalam kunjungan saya ke Hong Kong Agustus ini, segala hal masih begitu menegangkan. Sisa-sisa plang protes di kereta bawah tanah masih terlihat, bersama dengan kumpulan sejumlah aktivis dalam aksi mogok di pertengahan pekan; memperlihatkan bahwa gerakan ini bukannya tanpa perpecahan. Terlepas dari fokus dan tujuan protes tersebut, yakni untuk menantang cengkeraman China di pulau itu, ada keganjilan yang hadir seperti penampakan bendera Amerika.
Akhirnya masyarakat Goa tidak diberi pilihan dalam hal kemerdekaan tanah mereka sendiri.
Penyamaan simbolik antara Amerika Serikat dengan demokrasi ini cukup mengherankan, terutama di tengah tersiarnya informasi mengenai panggilan telepon Presiden Trump ke Ukraina. Lebih jauh lagi, ada sejumlah serangan terhadap para pengujuk rasa, yang menunjukkan bahwa tidak semua orang di sana punya pikiran yang sama.
Ketika saya menyaksikan sejarah yang dibongkar di Hong Kong, saya merasa diperlihatkan seperti apa jadinya kalau masyarakat Goa dulu mempertanyakan kolonialisme yang mereka hadapi pada paruh pertama abad ke-20, meski ada kelompok yang berselisih dengan satu sama lain.
Saya kagum dengan kemampuan pengorganisiran anak-anak muda Hong Kong di jalanan dalam mengumpulkan kehadiran begitu banyak orang di banyak titik di kota tersebut.
Di zaman mereka, bagaimana masyarakat Goa saling mengabarkan tentang pertemuan-pertemuan rahasia sekaligus berbagai aksi? Pertanyaan seperti ini biasanya tidak termuat dalam buku sejarah yang sekarang dibaca para siswa di Goa. Yang menjadi fokus sekarang adalah menanamkan warisan nasional yang monolitik dengan kecenderungan sayap kanan.
Pada tanggal 12 Agustus, yakni hari terakhir saya di Hong Kong, sebuah protes besar-besaran meletus. Aksi yang berlangsung benar-benar sebuah eksekusi politik yang jenius. Para pengunjuk rasa ini mengambil alih bandara untuk menarik perhatian internasional.
Ketika saya mencoba untuk naik kereta ekspres dari Stasiun Hong Kong, sejumlah pengunjung rasa berpakaian hitam mendesak saya dan para wisatawan lain untuk kembali. Salah seorang dari mereka menjelaskan bahwa mereka tidak ingin saya kena masalah di bandara. Saya cukup terharu dibuatnya, menyadari perempuan ini tidak lebih tua usianya ketimbang para mahasiswa saya—usia yang sama saat saya datang ke kota ini untuk pertama kalinya.
Saya mencoba menelepon maskapai saya, tetapi tidak tersambung. Di situs mereka masih terlihat bahwa penerbangan saya masih akan berangkat tepat waktu. Perjalanan singkat dengan kereta api ke Bandara Internasional Hong Kong itu membawa saya bertatap muka langsung dengan sepasukan pengunjuk rasa damai, yang kemudian bereskalasi begitu seorang perempuan muda kehilangan mata dalam bentrokan antara polisi dan demonstran.
Sehari sebelumnya, polisi menembakkan peluru bean-bag ke arah demonstran di Tsim Sha Tsui. Salah satu peluru menghantam wajah seorang perempuan muda, membutakan matanya. Di tengah lautan para pengunjuk rasa dan para pelancong yang malang, tak ada satu pun perwakilan maskapai yang bisa ditemui. Malam itu, tak ada satu pun pesawat yang terbang meninggalkan Hong Kong.
Saya merasa melihat sekilas seperti apa jadinya ketika masyarakat Goa menyusun pertanyaan mereka sendiri tentang kolonialisme.
Saya meninggalkan bandara dan menuju rumah seorang teman. Baru pada hari berikutnya maskapai mengabari rencana penerbangan baru. Saat kembali ke bandara, saya kembali melihat demonstran di mana-mana. Saya sempat berpikir bahwa saya tidak dapat pergi ke Goa lagi hari itu.
Sebagaimana perjalanan pertama yang saya lakukan ke Hong Kong, sekali lagi saya bepergian di antara dua bekas koloni Eropa. Pada titik berbeda, keduanya berbagi sejarah berupa penyetiran nasib politik oleh orang-orang yang bukan dari tanah mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, saya berhasil keluar dari Hong Kong. Begitu mendarat, saya baru tahu bahwa penerbangan yang dijadwalkan sesuai penerbangan saya telah dibatalkan.
Selama tiga dekade terakhir, saya telah berada di tiga momen paling penting dalam sejarah kontemporer Hong Kong: pra- dan pasca- serah terima wilayah, masa kini, dan semasa revolusi baru ini. Fakta bahwa anak-anak muda Hong Kong yang berada di garis depan sangatlah mencolok. Ada kemiripan yang terjadi dengan peristiwa politik lain dalam sejarah, yakni ketika anak-anak muda memimpin gerakan seperti pada era Hak Sipil tahun 1950 dan 1960-an di Amerika Serikat.
Tapi, kita bisa mengambil contoh kepemimpinan anak muda bukan cuma dari apa yang terjadi di masa lalu. Saat ini, kepemimpinan anak muda telah menarik perhatian di tengah persoalan paling mendesak kita sekarang ini: perubahan iklim.
Bahkan, revolusi yang dipimpin kaum muda Hong Kong menyingkap lebih banyak hal ketimbang dampaknya sendiri. Dalam refleksi saya, perjuangan ini mengingatkan saya pada pergulatan Goa dengan kolonialisme. Jika masa-masa ini bisa menjadi celah bagi Hong Kong untuk melihat kembali ke masa lalu, protes-protes yang berlangsung memungkinkan kita untuk melihat banyak tempat lain di dunia, di mana aksi-aksi politik berlangsung tanpa henti, namun luput dari pandangan.
Bulan Juli tahun ini, saya mengunjungi Hebron di Palestina dan belajar dari kelompok anti-kekerasan bernama Youth Against Settlements yang tengah berjuang melawan serbuan pendudukan Israel di kampung halaman mereka. Lebih dekat ke Goa, pada 5 Agustus—saat saya tiba di Hong Kong—India membatalkan status khusus wilayah Kashmir yang dipersengketakan. Dengan demikian, mereka menghapuskan selubung demokrasi yang tadinya dipertontonkan oleh India di wilayah tersebut. Seperti halnya di Palestina, para aktivis Kashmir terus menentang segala upaya perampasan hak yang mereka alami, bahkan ketika komunitas internasional tidak memandang mereka.
Serupa dengan berbagai wilayah lain di dunia, apa yang kita saksikan dari Hong Kong adalah persoalan yang terus ada dari sejak masa kolonial hingga pada kebangkitan nasionalisme pascakolonial. Apa yang kita turut saksikan adalah masa-masa ketidakpastian bagi masa depan Hong Kong.
Antara sejarah dan masa depan, saat ini Hong Kong tengah berlabuh di masa perubahan yang mendalam. Dalam kekuatan protes yang ada sekarang, masyarakat Hong Kong memvalidasi kemampuan minoritas untuk bersuara dalam menentukan nasib tanah mereka sendiri, dan dengan demikian, mengingatkan kita pada banyak perjuangan serupa di berbagai tempat lainnya di dunia.